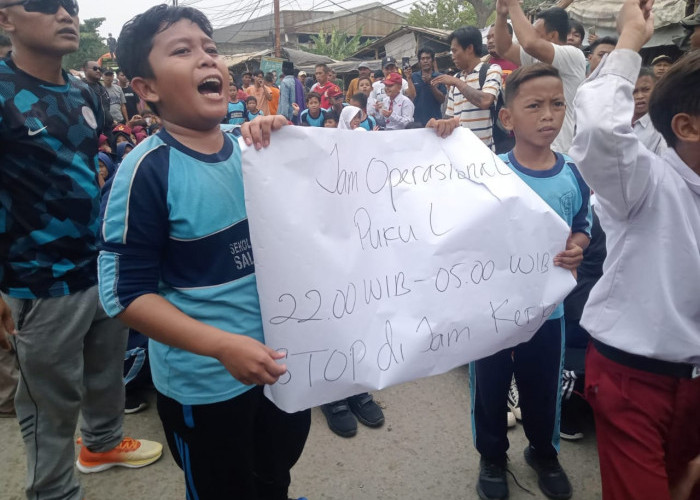Patah Hati Terhebatku

Adalah aku. Seorang pelayar di tengah lautan yang hampir karam sebab tak lagi bisa bertahan di tengah hantaman badai dan kehilangan arah jalan pulang sebab gulita menelan dunia tanpa purnama. Tiada lagi kucari jalan, hanya waktu yang membawaku pada kematian adalah yang teramat yang kunantikan. Aku muak dengan gemerlap semesta yang penuh kepalsuan. Aku paham betul, sebab beberapa tahun silam adalah tragedi temu pisah yang saling berganti mengajari arti kehidupan yang singkat dan terlalui sedikit untuk bisa dinikmati. Mah, pah, aku akan menyusul kalian nanti. Tinggal menghitung hari yang tak lama lagi, seperti saat kalian denganku di dunia waktu itu. Bukankah begitu singkat sampai aku tak menyadari betapa cepatnya hingga aku tak bisa berbagi waktu?. “Jika kamu rindu, kamu bisa menemuiku nanti malam. Yaitu dalam mimpi setelah sujud dalam Shalat di sepertiga malammu.” katamu berbisik lirih di telingaku. Aku mengangguk lesu. Jelas saja otak dan hatiku beradu pada waktu itu. Aku menyembunyikan resah dibalik senyum tipisku, untukmu kusembunyikan lukaku. Adalah kau. Cahaya yang menunjukkan sepanjang jalanku. Menuntunku pada titik terang menuju harap diantara segala keresahanku. Pelangi yang kembali warnai bumiku setelah hampir kehilangan setengah nafas sebab menggigil kedinginan terguyur hujan. “Suatu hari, aku kan pergi dan kau pun kan hilang. Dan tempat ini hanya akan menjadi kenangan.” Ucapku parau. Aku menatapmu lama, begitupun sebaliknya. Dalam diam seribu bahasa. Masing-masing dari kita saling mengartikan arti detakan jantung yang lebih cepat dari biasanya. Kita adalah sepasang yang akan saling menangisi jejak saat tiba saatnya kita berpulang pada teduhan yang tak sama. Sebab, orang tuamu yang tidak pernah bisa menerimaku apa adanya. Kata mereka, aku hannyalah seorang gadis yang tak jelas asal usulnya. Kata mereka pula, aku adalah seorang gadis yang tak jelas masa depannya. Dan kau yang telah berjuang sekuat-kuatnya untuk meluluhkan hati mereka, hasilnya justru aku yang menerima batunya. Sebab harus menerima di caci maki agar tahu diri. “ Jangan ganggu anakku lagi, jangan mencoba mendekatinya atau kamu tidak akan pernah lagi melihatnya.” Suara itu, kembali memutar di ingatan membuat bendungan sungai kecil di bawah mataku tak lagi kuat menahan bebannya. Aku menangis, sakit teramat dalam kurasakan. “kamu kenapa?” tanyamu sontak. Lalu seketika aku kembali menghapus derasnya bulir bening di pipiku. Aku menggeleng dan berusaha menyunggingkan senyuman. Perihal ancaman itu, aku tak pernah berniat untuk mengatakannya padamu. Tak apa, cukup aku yang menanggung sakitnya. “Aku mencintaimu,” kataku. Dan kau membalasnya dengan senyuman. Entah kau lupa atau sengaja tak ingin lagi mengungkitnya gerangan apa yang membutaku menangis baru saja. ** Desember kedua. Tahun di mana semua yang terasa begitu dekat perlahan berjarak dan banyak sekat. Aku dan kamu, tak lagi menjadi kita dalam peran yang sama. Melainkan sepasang rahasia rasa yang terkutuk semesta. Bukan lagi kita, tapi mereka semua tahu takdirnya. Hubungan kita sudah terancam usai ditelan masa yang tak memberi kesempatan banyak meski untuk saling bertatap dan bersua berbagi harap. Kita menjadi saling bisu. Kita menjadi asing, meski di belakang layar aku masih menyimpan namamu di bagian terpenting. Hari demi hari berlalu, tak kutemui lagi dirimu. Sejujurnya, aku merindu. Di tempat biasa kita bersua, di bawah rindang pohon yang menjadi tempat teduhan paling nyaman saat hujan, aku mengulang kembali lagu kesukaan kita. Memori setahun silam kembali memutar kenangan. Aku menyepi dalam keramaian. Aku sendiri dirundung kegelisahan. Akankah, ini adalah detik-detik terakhir apa yang kutakutkan menjadi kenyataan? “oh kasih jangan kau pergi, tetaplah kau selalu disini. Jangan biarkan diriku sendiri, larut di dalam sepi, larut di dalam sepi...” Sepenggal lirik itu serasa nyaring terdengar ditelinga, aku menjerit kecil, perih rasanya. Bagaimana bisa, kau dulu menyanyikan lagu itu untukku, sedangkan kau sendiri yang berlalu dariku. Sial, aku tidak bisa lari dari kisahku denganmu. “Hari Rabu, Hanz akan datang ke kampus. Tapi bukan untuk mengikuti kelas seperti biasa, melainkan untuk mengurus segala kepindahannya. Sekaligus langsung pamit pada kita semua.” Suara itu tiba-tiba saja membuyarkan segala lamunan. Samar terdengar. Itu suara Fauzi, sahabat Hanz. “Apa?” tanyaku kemudian memastikan kabar buruk yang tadi kudengar apa benar, atau hanya sebuah halusinasi ketakutan? “Hari Rabu Hanz Awal berhenti dari kampus kita ini untuk melanjutkan kuliahnya di luar Negri.” Ucapnya kembali. Jelas saja aku seperti tersambar petir di siang bolong. Dadaku nyeri serasa terhantam benda tajam. Biadab sekali apa yang dia putuskan tanpa bertanya perihal keikhlasan yang mungkin tidak pernah kuberikan. “Omong kosong macam apa itu?” kataku, menatap tajam ke arah Fauzi yang setengah gelagapan. “Terakhir, kata Hanz maaf dan terimakasih, itu saja.” Ucapnya kemudian. Lalu ia pergi tanpa menunggu jawabku kemudian. Sesingkat itu. Kalimat-kalimat terhebat yang mampu menghujam seluruh jantungku. Rasanya terkoyak, tersayat, lebih dari itu. Entah, sebuah sakit yang tak bisa kuutarakan lewat perantara kata. “Tidak,,!” aku mendesis lirih. Mencoba menata setengah kewarasanku yang hampir lebur bersama kabar terburuk itu. Ingin rasanya aku lari dan mencacimu seraya menangis, menjerit dan meneriakkan namamu lantang. Menampar wajahmu, memukulimu dan apapun itu aku ingin mengatakan apapun padamu. Tapi apalah daya, aku bukan siapa-siapa untuk melakukan hal semacam itu. *** Lembayung menyeret matahari ke dalam lubang lautan. Camar beringsut meninggalkan bibir pantai. Perlahan hari berganti malam. Di kesunyian aku bertarung melawan sepi. Meratap dan mengasingkan diri, dengan mata jingga adalah rutinitasku setelah kau tiada. Sebagaimana senja yang hadir lalu tiada, aku menemukan sajak-sajakku diantara hadirnya. Indah, fana. “Kehadiranmu adalah maha karya Tuhan tatkala semesta sedang membagi bahagianya. Dan kehilanganmu adalah kutukan yang membawa setengah kewarasanku yang mengajariku patah hati yang sebenarnya.” gumamku lirih, berbicara pada diri sendiri. Esok, Rabu tiba. Hari yang akan menjadi sejarah patah hati terhebatku. Saat kau beranjak pergi meninggalkanmu dan menjadikan ketakutanku sebagai kenyataan terpahit dalam hidupku. Aku menunggumu Hanz, tapi kali ini bukan untuk ucapkan selamat datang, melainkan selamat jalan. Kekasih rahasiaku. Lain dari pada kegilaan-kegilaanku padamu. Aku menemukan senandika bersama air mata kehilanganmu. Hanz, aku menemukanmu di tengah badai untuk kita saling berpegangan dan menguatkan. Dan pada akhirnya, kita harus berpulang pada kenyataannya bahwa kita bukanlah satu tujuan arah kepulangan. *** Rabu kelabu menyapa embun di pagi buta. Aku menantimu di balik gerbang biru kampus kita tempat kita bertemu pertama kalinya. Aku tahu, kau takkan berlalu tanpa meninggalkan jejak air mata di tempat kenangan itu. Sebuah Fazero sport tiba. Itu adalah mobilmu.. Aku memejamkan mata lebam sebab gadang semalaman. Aku dapati kau keluar dengan orang tuamu. Kau, memakai setelan jas hitam favoritmu. Tampak begitu indah rupamu Hanz, siapakah gerangan yang nantinya akan menjadi pemilik pelukmu yang sempurna hangatnya itu. Ya Allah, ikhlaskanlah aku. Kau menyadari kehadiranku di tempat itu. Kau menolehku sejenak, lalu kemudian memalingkan wajahmu cepat. Aku muak. Aku terpukul hebat. Kali ini ketabahanku di uji hebat melepasmu dengan sakit yang menyayat. “Hanz “ teriakku. Seketika tak hanya kamu, tapi juga orang tuamu ikut menolehku. “Aku mencintaimu.” Tapi tak apa, pergi saja. Kebisuan dan jarak yang kau cipta akhir-akhir ini mulai membuatku terbiasa tahu diri dan terasing dari hubungan yang dulu begitu hangat dan kubanggakan. Aku melepasmu dengan ikhlas, semoga pelangi barumu jauh lebih hebat perihal mewarnai harimu, daripada aku yang hanya mempunyai hitam putih dan abu-abu. Bunda, ayah, terimakasih telah mengajariku pelajaran paling berharga perihal tahu diri. Dan cinta bukan untuk saling memiliki. Aku selalu percaya keajaiban itu ada, tapi kali ini aku saksikan, semuanya mesti selaras dengan logika.” Ucapku dengan berani. Membuat semua mata tertuju pada sepasang mata sendu ini. Dan kamu Hanz, sekali lagi hanya mampu diam. Tiada yang ingin kusalahkan. Manusia di seluruh bumi ini semestinya tahu, ridho orang tua selalu berada di atas segalanya. Aku adalah orang baru untukmu. Kau telah memilih keputusan yang benar untuk meninggalkanku demi orang tuamu. Kau menghampiriku. “Terimakasih perempuan terhebatku. Maafkan aku untuk segala lukamu. Aku pamit. Kita tidak bisa bersatu di dunia, aku menunggumu di pelukan dimensi kedua kelak. Seperti sebelum kau mengenalku, mari kita lalui masa ketika menunggu akhir dari yang fana dan menuju bahagia yang sesungguhnya.” Ucapmu. Dan kutemui matamu mulai merah muda. Aku tersenyum tipis menahan pedihku. “Denganmu aku menemukan segalanya, karenamu aku berpulang dengan luka.” Kataku. Terakhir kali kalimat itu akan menjadi penutup sajakku dalam nuansa patah hati yang sebenarnya. Kemudian kau beranjak perlahan. Mengurusi segala perihal kepindahan. Pamit pada semuanya. Aku menutup mata. Esok, lusa, dan seterusnya. Aku tak akan pernah lagi melihatmu kembali. Benar kataku, tiada yang abadi. Penantian yang sebenarnya pasti adalah menunggu mati. Cahaya kan redup, warna kan memudar, api kan padam, pasang kan surut, pertemuan pasti berujung perpisahan. Dan itu adalah sebuah proses yang sebenarnya dalam kehidupan. Terakhir, kau menolehku kembali. Aku berpaling, tak kuasa dengan segala apa yang kurasa. Kau dan orang tuamu kembali masuk dalam mobilmu, lalu melaju. Lenyap, hilang dalam pandangan. Aku bersimpuh di bawah langit sang Khaliq, dengan air mata yang membanjiri pipiku. Selamat tinggal Hanz, selamat tinggal untuk kembali dalam perjumpaan dan kebersamaan yang kekal. [Red/Akt-45] Aktual News Penulis by : Dristy Aulia
Sumber: